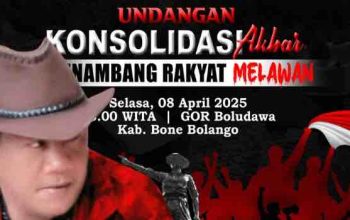Kuasa Masyarakat VS Kuasa Kepala Desa
Oleh : Bekrand Kolosovic (Buruh Sosial Desa)
Hingga tahun 2018 pemerintah pusat melalui APBN telah menggelontorkan anggaran kurang lebih sebesar 180 Triliun kepada kurang lebih 74.000 desa diseluruh indonesia dan dalam rancangan APBN 2019 yang teralokasi sekitar 73 trilyun, jumlah dimaksud belum termasuk dana perimbangan sebesar 10 %, bagi hasil retribusi dan bantuan keungan.
Aggaran yang begitu fantastis tersebut dialokasikan secara bertahap sejak Tahun 2015 dengan dasar pijak pelaksanaan adalah UU No. 6 tahun 2014, “anggaran tersebut diperuntukan untuk desa bukan untuk kepala desa” mengutip perkataan Menteri Keungan SRI Mulyani, sebagai bentuk himbuan bagi masyarakat agar iktut serta mengawasi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sejauhmana keterlibatan dan pelibatan masyarakat sejauh ini?
Dana desa (APBN) adalah amanah UU No, 6 Tahun 2014 sebagai wujud komitmen dan pengakuan negara atas keberadaan desa sebagai konsekuensi pemberian azas rekognisi dan subsidaritas, UU 6 Tahun 2014 telah memisahkan sistem pemerintahan desa keluar dari pemerintahan daerah (otonom) yang sebelumnya terkoptasi dalam UU 32 Tahun 2004, akan tetapi dalam implementasinya harapan agar desa mandiri serta tumbuh sesuai dengan karakteristik dan lokalitasnya masi jauh dari harapan, dalam UU Desa pengertian dan konsep desa telah dikontruksi secara ideal sehingga menghasilkan definisi, desa adalah masyarakat yang berpemerintahan yang mengandung pengertian bahwa hal pertama yang utama membentuk unsur desa adalah masyarakat bukan pemerintahan, akan tetapi dalam praktek regulasinya yang tertuang dalam PP 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP 47 Tahun 2015 dan Permendagri lebih menonjolkan aspek pemerintahan ketimbang masyarakat sebagai reperesentasi unsur sosial budaya serta pranata di desa.
Desain regulasi tentang system pemerintahan desa seakan akan mendikotomikan antara pemerintah desa dan masyarakat bahkan memperlemah posisi tawar masyarakat dan kelembagaan lainnya dalam pembangunan desa.
Alhasil produk dari desain sistim pemerintahan desa seperti ini cenderung teknokratis tidak ubahnya seperti SOPD tehnis pemerintahan daerah yang hanya melaksanakan kegiatan pembangunan secara tehnis berdasarkan arahan regulasi dan sinkronisasi program kegiatan dari level pemerintahan yang ada di atasnya.
Harapan bahwa UU Desa untuk memanadirikan desa dan masyarakat berdasarkan kewenangan dan potensi masih sebatas mimpi dan upaya untuk memperpendek rentang kendali birokratis kebijakan dan penganggaran terhadap masyarakat dan upaya pelibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa masih jauh dari harapan, pemerintah desa justru terdorong menjadi ekslusif dan cenderung tampil sebagai (new determinator) dan cenderung mencontoh dan mejalankan fungsi kurang efektif, infolutif dan instransaparan dan tidak demokratis dalam penyelenggaran pemerintahan seperti level pemerintahan yang ada di atasnya.
Dalam UU Desa desain sisitim pemerintahan desa adalah hybrid konsep local self goverment dengan self community goverment menjadikannya ambigu dan timpang dalam praktek peran dan fungsi peran pelayanannya. Desain sistim Pemerintahan desa sebaiknya berkonsep tunggal self comunity goverment dalam rangka untuk mempertahankan kultur demokrasi dan peran penuh partisipasi masyarakat dengan menekankan sistim demokrasi deliberasi dalam wujud musyawarah bukan perwakilan atau perwalian.
Contoh kasus dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 114 Tahu 2014, peran masyarakat terbatas pada perencanaan pembangunan desa, pada saat pembahasan dan penentuan anggaran masyarakat tidak wajib lagi untuk dilibatkan karna telah menjadi ranah pembahasan dan persetujuan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Hal lain adalah adanya dikotomi hasil kesepakatan partisipatif dalam musyawarah pembangunan desa dengan visi kepala desa terpilih yang nota bene tidak terkorelasi. Dengan konsep desain tunggal sistim pemerintahan desa menjadikan desalah yang mempunyai visi misi bukan kepala desa.
Dalam pengelolaan anggaran Idealnya kuasa anggaran harus bersifat kolektive (Musyawarah), penentuan terhadap kebijakan pembangunan tersebut melalui keputusan bersama (partispatif) konsepsinya adalah untuk menarik masuk peran masyarakat dalam kontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memperkuat peran BPD dan masyarakat, bukan sebaliknya kuasa anggaran terpusat pada satu orang (Kepala Desa) atau berada pada satu lembaga dan menghilangkan unsur semangat kolektivitas desa serta menimbulkan “kerawanan” permasalahan di desa.
Tawaran konsep desain sistim pemerintahan desa sepert sistim pemerintahan komunitarian dimana kuasa kebaijakan dan anggaran berada di tangan masyarakat dalam musyawarah, visi misi yang dijadikan acuan pembangunan bukanlah visi misi kepala desa melainkan visi misi desa, Badan permusyawaratan desa berperan sebagai pengawas pelaksana pemerintahan yang ditugaskan oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh masyarakat, dengan demikian pemerintah desa dan BPD terdorong beratnggung jawab penuh kepada masyarakat bukan hanya kepada pemerintah yang ada di atasnya.
Desain sisitim pemerintahan desa seprti ini sangat demokratis sebagai mewujudkan slogan yang kental dari oleh dan untuk masyarakat, memungkinkan peran masyarakat dalam pembangunan secara penuh dalam pengambilan kebijakan dan arah pembangunan, memastikan bahwa community power berjalan sesuai harapan yang akan melahirkan kontrol penuh terhadap kegiatan pembangunan desa, bukan malah sebalinya dalam praktek selama ini yang justru meperkecil ruang partispasi dan cenderung mendelagasikan dan mewakilkannya kepada Badan Permusyaratan desa dan pemerintah desa.