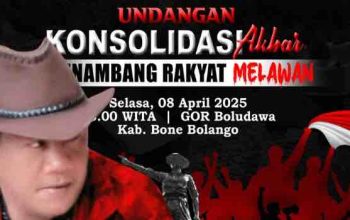Faktanews.com – Jakarta, tiga tahun yang lewat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tembus 1 triliun dollar AS (USD). Walhasil, Indonesia masuk daftar elit: kelompok negara dengan PDB di atas 1 triliun USD di dunia alias trillion–dollar club.
Jangan salah, hanya 16 negara di bawah kolong langit ini yang punya PDB bernilai triliunan dollar. Saking bangganya, Presiden Joko Widodo pernah bilang, “jangan kita minta lagi bantuan negara-negara lain, kita sudah saatnya membantu negara lain.”
Di waktu yang lain, Presiden Jokowi pernah mengingatkan bangsa ini agar tak kufur nikmat. Sebab, ketika pertumbuhan ekonomi di banyak negara hanya di kisaran 0-3 persen, Indonesia masih di atas 5 persen.
Sampai kemudian, datanglah pandemi virus korona. Pandemi adalah ujian. Bukan saja menguji daya tahan sistem kesehatan kita, tetapi juga imunitas ekonomi nasional kita. Pada aspek ekonomi, ujiannya jelas: seberapa tangguh negara dengan PDB 1 triliun USD ini menghadapi dampak pandemi?
Namun, apa mau dikata, PDB di atas 1 triliun USD itu bak butiran debu ditelan pandemi. Angka ajaib itu tak banyak menolong di masa pandemi. Tak membuat masker diproduksi massal dan dibagikan gratis. Tidak berhasil membuat semua tenaga medis kita terlindungi oleh alat pelindung diri (APD).
Ini yang lebih ironis. Di Indonesia, negeri ber-PDB di atas 1 triliun USD, tak semua tes covid-19 itu gratis. Hanya yang positif dan butuh perawatan intensif di RS yang ditanggung oleh BPJS.
Sementara tes mandiri, yang diperlukan sebagai syarat bepergian atau kebutuhan lain, tetap berbayar. Dan itu tidak murah. Biaya rapid test itu di kisaran Rp 100-400 ribu. Sedangkan tes PCR/swab di kisaran Rp 1 juta ke atas. Bahkan ada RS yang memasang sistem paket: silver, gold, platinum.
Bandingkan dengan Venezuela, negeri yang kerap jadi referensi “failed state”. Sejak 2014 hingga sekarang, PDB-nya terus anjlok. Pada 2018, PDB-nya hanya 305.46 milyar USD—50 kali lebih kecil dari PDB Indonesia. Tapi, di Venezuela, semua tes digratiskan oleh negara.
Sekarang, lihat gelontoran stimulusnya untuk menangani pandemi. Nilai stimulus Indonesia, yang berjumlah Rp 695,2 triliun, hanya 4,6 persen dari PDB kita. Itu pun yang jatuh ke sektor kesehatan, bantuan sosial, dan UMKM hanya di kisaran Rp 413 triliun atau 2,7 persen dari PDB.
Walakin, itu terlalu kecil bagi ukuran negara penganut Pancasila. Bandingkan dengan Singapura, negeri kecil yang sangat kapitalistik itu, paket stimulusnya tembus angka 20 persen dari PDB[2].
Malaysia, negara tetangga kita, hingga 10 Juni 2020, paket stimulusnya juga menyentuh 20 persen. Sementara Thailand, tetangga kita yang lain, stimulusnya di kisaran 1o persen dari PDB.
Di jejeran negara G-20, hingga Juni 2020, Indonesia juga berada di papan bawah. Sangat jauh dari Jepang (21 persen), Amerika Serikat (12,2 persen), dan Australia (8,5 persen).
Konsep Perang
Simon Kuznets, seorang ekonom dan ahli statistik, disebut-sebut sebagai bapak penemu konsep PDB.
Saat itu, tahun 1930-an, sebagai Kepala Biro Nasional Penelitian Ekonomi (National Bureau of Economic Research), dia ditugasi mencari metode menghitung pendapatan nasional.
Saat itu, di tengah cekikan depresi besar (great depression) dan perang, pemerintah butuh pegangan data untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
Tahun 1940-an, ketika Inggris berperang melawan fasisme Jerman, John Maynard Keynes mengembangkan konsep ini dalam konteks kebutuhan perang: menghitung kapasitas Inggris dalam memobilisasi sumber daya dan daya tahannya dalam perang.
Keynes, yang kala itu bekerja di Departemen Keuangan Inggris, mengembangkan konsep PDB ini dengan menghitung konsumsi swasta, investasi, dan belanja pemerintah dalam perhitungan pendapatan nasional.
Jadi, terang-benderang lah bahwa PDB adalah produk perang. Dan itu diakui oleh Kuznets sendiri. “PDB adalah konsep yang dirancang di masa perang untuk melihat kapasitas permintaan dan pasokan ekonomi. Untuk waktu yang lama, kami tahu ini ada kekurangan,” jelas Kuznets seperti dikutip Diane Coyle, penulis buku GDP: a Brief But Affectionate History.
Namun, setelah Konferensi Bretton Woods tahun 1944, konsep PDB mulai diadopsi banyak negara. Terutama sejak IMF dan Bank Dunia menggunakan PDB sebagai alat ukur kemajuan ekonomi sebuah negara.
Bukan Ukuran Kemakmuran Rakyat
Sederhananya, PDB adalah nilai moneter dari semua produksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu.
Penghitungan PDB hanya pada aktivitas produksi, distribusi, dan komsumsi barang dan jasa yang melibatkan uang. Jadi, jika kamu berproduksi, lalu dikonsumsi sendiri, itu tak masuk hitungan PDB.
Di sinilah letak masalah pertamanya. Ada banyak aktivitas ekonomi yang tak dihitung dalam PDB, seperti kerja tak dibayar (kerja domestik dalam rumah tangga, kerja pengasuhan/perawatan, dan kerja-kerja sosial), kerja yang tak dibayar dengan uang, produksi barang yang tak dijual, pasar gelap, dan aktivitas barter barang dan jasa.
Oiya, kerja sebagai aktivis pergerakan rakyat, sekalipun bekerja 24 jam untuk membela dan mengadvokasi hak-hak rakyat, sepanjang menjadi kerja tak berbayar, tidak masuk hitungan PDB.
Di negara yang mayoritas perempuannya bekerja gratis sebagai pengurus rumah tangga, tentu PDB-nya menjadi sangat maskulin sekali. Padahal, berdasarkan hitungan Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender, kerja domestik dan kerja perawatan tak berbayar berkontribusi antara 10 hingga 39 persen padaPDB.
Masalahnya juga, PDB hanya menghitung produksi yang menghasilkan barang-dagangan alias komoditi. Sehingga, produksi untuk kebutuhan sendiri, sekalipun itu sangat penting, itu tak dihitung.
Jadi, benarlah apa yang dikatakan aktivis Vandhana Shiva: “pertumbuhan PDB hanya mengukur hutan yang dikonversi menjadi uang tunai. Dan barang milik bersama menjadi komoditi.”
Karena logikanya, produksi apa saja asalkan mendatangkan uang, maka konsep PDB mengabaikan aspek positif dan negatif dari produksi.
Sebagai contoh, produksi dan belanja mobil itu positif bagi PDB, tetapi menghasilkan emisi yang merugikan lingkungan dan kesehatan publik.
Contoh lain, gencarnya investasi ke sektor ekstraktif, seperti perkebunan, menjadi salah satu motor pertumbuhan PDB Indonesia. Tetapi, hampir setiap tahun Indonesia menanggung bencana yang ditimbulkannya, seperti banjir, longsor, dan kabut asap.
Contoh lainnya lagi, apa yang disinggung oleh Karl Marx dalam Capital, sesuatu dikonversi menjadi barang-dagangan boleh jadi karena dua faktor: kebutuhan atau fantasi. Jadi, tak melulu produksi itu berbasis kebutuhan, bisa juga karena fantasi yang tercangkokkan pikiran kita lewat iklan-iklan di media massa.
Nah, ada satu aspek penting lagi yang tak bisa ditangkap oleh PDB: ketimpangan ekonomi. Boleh jadi, sebuah negara dipuja-puji karena PDB-nya yang meroket, tetapi ketimpangan ekonominya juga melebar.
Tidak usah jauh-jauh mencari contoh, negara kita jadi contohnya. Sepanjang 2000-2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia sungguh menakjubkan: rata-rata di atas 6 persen per tahun. Namun, dalam rentang waktu yang sama, rasio gini kita juga melebar tajam dari 0,30 menjadi o,45.
Dan yang terpenting: PDB tak bisa jadi alat ukur kemakmuran. Oke, kita patut berbangga dengan PDB Indonesia yang tembus 1 triliun USD, tetapi ada 24,14 juta rakyat Indonesia yang hidup hanya dengan Rp 450 ribu per bulan (garis kemiskinan).
Merujuk ke laporan Bank Dunia, ada 115 juta orang atau 45 persen dari populasi (aspiring middle class) yang hidup dengan Rp 532 ribu hingga Rp 1,2 juta per bulan. Kemudian, ada 24 persen kelompok rentan (vurnerable) yang hidup dengan Rp 354 ribu-Rp 532 ribu.
Jadi, kalau digabungkan semuanya, hampir 80 persen rakyat Indonesia masih “rawan” dengan kemiskinan. Itu pun, standar garis kemiskinannya (poverty line) sangat rendah.
Mengapa PDB yang tinggi tak berbarengan dengan peningkatan kemakmuran?
Sebab, PDB menghitung semua output ekonomi suatu negara, termasuk yang dihasilkan oleh invidividu atau badan usaha asing. Untuk negara dengan kontribusi investasi asing yang cukup besar, seperti Indonesia, tentu sulit menjadikan angka-angka PDB sebagai ukuran kemakmuran.
Alternatif PDB
Sejak 1970-an, Buthan, negeri kecil di Asia bagian selatan, sudah berusaha meninggalkan PDB.
Mereka kemudian memperkenalkan Indeks Kebahagiaan Nasional (Gross National Happines), yang menghitung banyak aspek penting dalam kehidupan manusia: standar hidup, kesehatan, ekologi, keragaman budaya, dan lain-lain.
Tahun 2008, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menugasi tiga ekonom handal, yaitu Joseph Stiglizt, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, untuk mencari alat ukur lain yang lebih mencerminkan kesejahteraan manusia.
Selandia Baru, di bawah kepemimpinan politisi perempuan yang progressif, Jacinda Ardern, juga beralih dari PDB ke konsep baru: anggaran kesejahteraan (well-being budget). Konsep baru ini menekankan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan anak, dan kesehatan mental.
Negara-negara OECD memperkenalkan konsep “Better Life Index”, yang memasukkan soal perumahan, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ekologi, kepuasan hidup, jam kerja, dan partisipasi warga negara.
Kemudian, ada konsep Genuine Progress Indicator (GPI). Konsep ini sebetulnya hanya menyempurnakan konsep PDB, dengan memasukkan biaya sosial dan ekologi yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi.
Singkat cerita, ada banyak konsep alternatif terhadap PDB ini. Saya kira, bangsa kita bisa merancang sendiri ukuran kemajuan ekonominya, dengan alat ukur yang sesuai dengan cita-cita nasional kita. (***)
Penulis : RUDI HARTONO, pimred berdikarionline.com
Artikel Ini sebelumnya Sudah Dimuat di berdikarionline.com